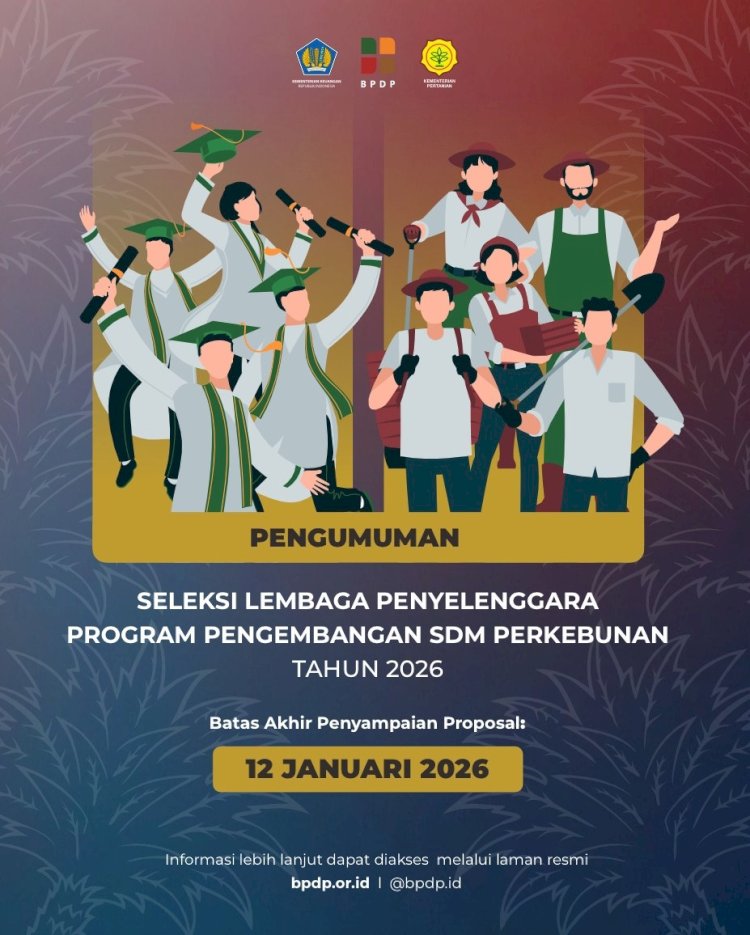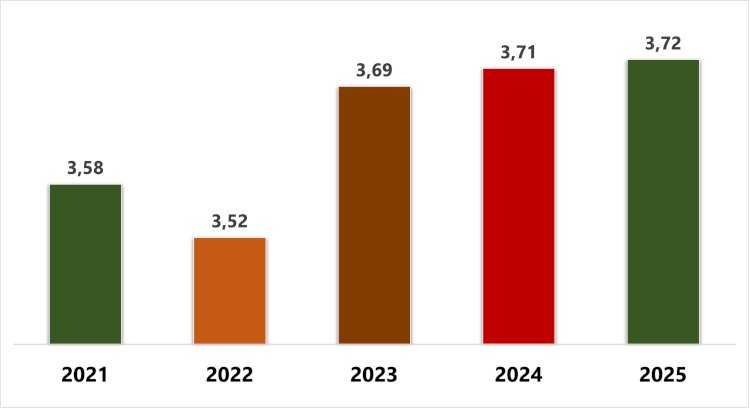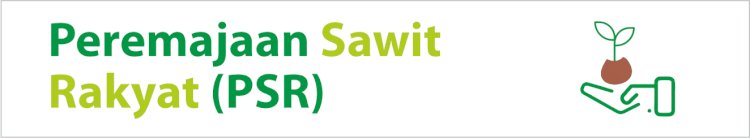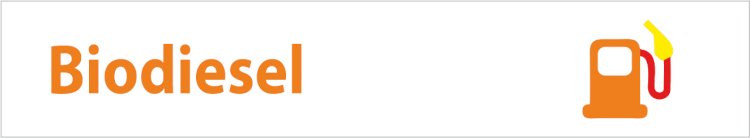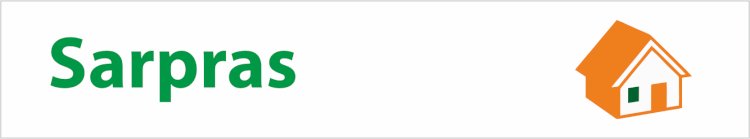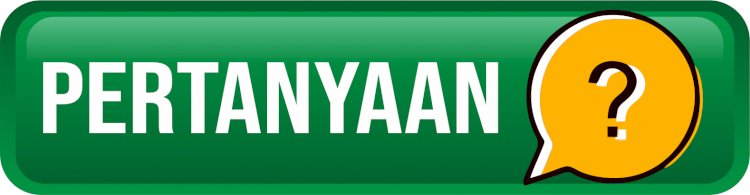Inklusivitas Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan kelapa sawit bersifat inklusif karena mampu menciptakan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun tak terlibat langsung dalam usaha perkebunan sawit.

Perkebunan kelapa sawit yang bersifat inklusif tidak hanya memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan perkebunan, tetapi juga masyarakat umum secara luas. Inklusivitas perkebunan kelapa sawit dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi.
PASPI Monitor (2024) dalam jurnal berjudul Perkebunan Sawit Inklusif menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit bersifat inklusif karena mampu mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pedesaan sehingga menciptakan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam usaha perkebunan sawit. Selain itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi daerah non-sawit.
Adapun, Bank Dunia (2013) dalam publikasi berjudul Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development mengungkapkan bahwa keberlanjutan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pertumbuhan hijau (green growth), tetapi juga harus bersifat inklusif. Keberlanjutan memerlukan indikator inklusivitas yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Berikut ini ulasan mengenai inklusivitas perkebunan kelapa sawit baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi yang dirangkum dari jurnal PASPI.
Inklusivitas Ekonomi. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui program transmigrasi guna menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam konteks pembangunan kawasan pedesaan tersebut merupakan kegiatan ekonomi pioner (PASPI, 2024).
Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan mendorong pengembangan berbagai kegiatan ekonomi yang menyediakan agroinput, jasa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan (Rifin, 2011; PASPI, 2023). Aktivitas perdagangan yang berkembang seperti jasa transportasi TBS atau CPO, jasa perbankan, kegiatan perdagangan sembako dan peralatan rumah tangga, hingga warung makan dan restoran.
Perkebunan kelapa sawit juga mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit baik swasta maupun BUMN membangun akses jalan (access road), jalan usaha tani (farm road), kebun inti dan plasma, perumahan karyawan, serta mendirikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga menyiapkan fasilitas umum bagi masyarakat.
Selain menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, perkebunan kelapa sawit juga memiliki potensi untuk mendorong sektor ekonomi lain. Berdasarkan data BPS (2022), nilai transaksi antara masyarakat perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat pedesaan mencapai sekitar Rp153 triliun per tahun. Nilai tersebut mencakup transaksi sebesar Rp98 triliun per tahun dengan petani tanaman pangan, Rp28 triliun per tahun dengan peternak, serta Rp27 triliun per tahun dengan masyarakat perikanan atau nelayan.
Inklusivitas Sosial. PASPI (2015) melaporkan bahwa sekitar 67 persen tenaga kerja yang terserap di perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah, sementara sisanya merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) ke atas. Secara umum, tingkat pendapatan yang diterima oleh karyawan yang bekerja di industri kelapa sawit berada di atas upah minimum regional (UMR).
Selain itu, industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha dalam skala luas. Sekitar tiga juta usaha keluarga, ribuan usaha menengah dan besar, serta ribuan pemasok barang dan jasa terlibat dalam rantai pasok industri ini.
Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri kelapa sawit mencapai sekitar 8,2 juta orang. Untuk indikator inklusivitas sosial, berbagai studi membuktikan bahwa dampak multiplier pertumbuhan perkebunan kelapa sawit cukup besar bagi pembangunan wilayah pedesaan maupun pengurangan kemiskinan.
Goenadi (2008) melaporkan bahwa lebih dari enam juta orang terlibat dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan berhasil keluar dari jerat kemiskinan. Sejalan dengan temuan tersebut, Edwards (2019) memperkirakan bahwa sekitar 2,6 juta masyarakat Indonesia keluar dari persoalan kemiskinan karena industri perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, riset Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019) menunjukkan bahwa sekitar 1,3 juta penduduk pedesaan dan 10 juta penduduk Indonesia secara keseluruhan berhasil keluar dari kemiskinan melalui pertumbuhan industri kelapa sawit sejak tahun 2000 silam.
Inklusivitas Ekologi. Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi layaknya paru-paru bumi dan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia.
Henson (1999) mengemukakan bahwa penyerapan bersih karbondioksida pada perkebunan kelapa sawit menunjukkan hasil signifikan, yakni mampu menyerap sebesar 64,5 ton CO2 per hektare per tahun secara neto. Selain itu, perkebunan kelapa sawit berperan dalam menyegarkan atmosfer bumi melalui pasokan oksigen dengan volume mencapai sekitar 448,8 juta ton O2 (PASPI, 2023).
Berdasarkan data USDA (2021), luas perkebunan kelapa sawit dunia pada tahun 2020 mencapai 24 juta hektare. Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi penting dalam membersihkan atmosfer bumi dengan menyerap karbon dioksida (carbon sink) sekitar 1,5 miliar ton CO2.
Kemudian minyak sawit telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati (biodiesel) guna mengurangi ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil. Penggunaan biodiesel sebagai pengganti solar terbukti mampu menurunkan emisi karbondioksida hingga 62 persen (European Commission, 2012).
Hal tersebut di atas menunjukkan kesuksesan inklusivitas ekologi industri kelapa sawit dalam mengurangi emisi serta menyerap karbon dari atmosfer bumi. Kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan menyerap karbondioksida dari atmosfer atau mengurangi emisi karbondioksida ke atmosfer dapat dikategorikan lebih inklusif secara ekologis apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang justru menghasilkan emisi karbon (PASPI, 2015).