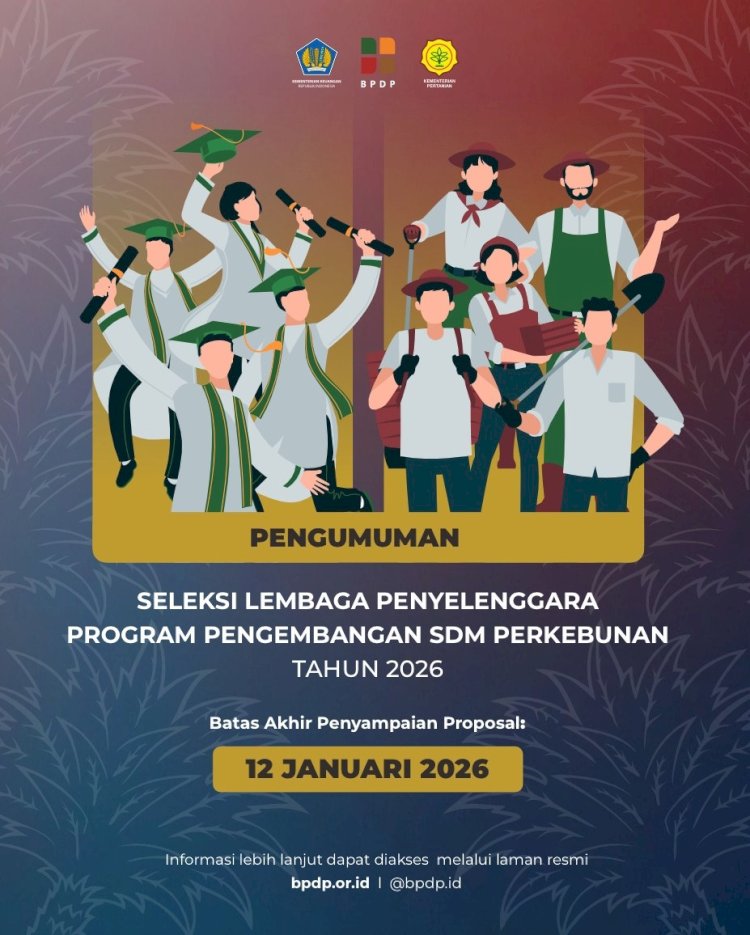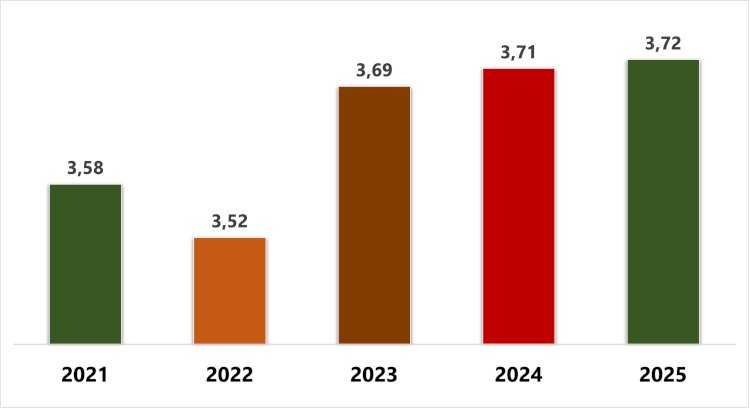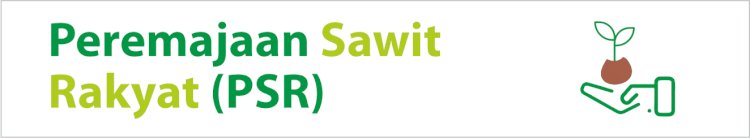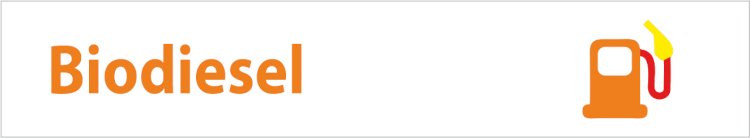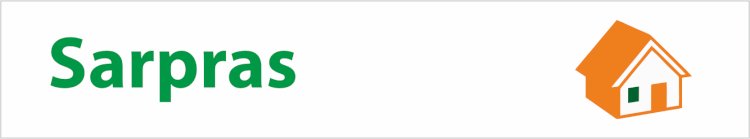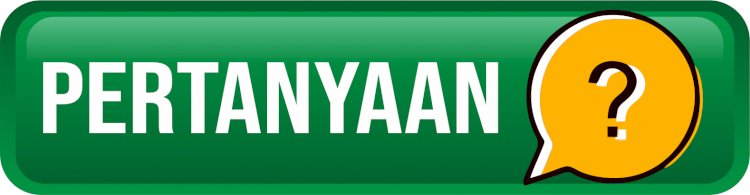Kontribusi Positif Industri Kelapa Sawit dalam Ekonomi Hijau
Industri kelapa sawit memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, arah pembangunan global menunjukkan pergeseran fundamental menuju paradigma keberlanjutan (sustainability) yang menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, paradigma tersebut terwujud dalam konsep ekonomi hijau (green economy) yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya, inovasi ramah lingkungan, serta inklusivitas sosial dalam proses pembangunan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi konsep ekonomi hijau sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan peningkatan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk adopsi SDGs dan upaya penurunan emisi karbon, transisi Indonesia menuju ekonomi hijau semakin nyata dalam satu dekade terakhir.
PASPI Monitor (2025) dalam jurnal berjudul Industri Sawit dalam Membangun Ekonomi Hijau di Indonesia mengatakan bahwa industri kelapa sawit memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep ekonomi hijau. Seiring dengan peningkatan tata kelola yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, industri kelapa sawit memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di Tanah Air.
Perkebunan kelapa sawit memiliki multifungsi yang terdiri atas white function, yellow function, green function, dan blue function (Aldington, 1998; Dobbs & Petty, 2001; Moyer & Josling, 2002; Huylenbroeck et al., 2007). Secara ringkas, white function menggambarkan fungsi ekonomi; yellow function mencerminkan fungsi atau jasa sosial dan budaya; sedangkan green function dan blue function merepresentasikan fungsi atau jasa lingkungan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan tata kelola air (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2020; 2021a).
Melalui proses fotosintesis, perkebunan kelapa sawit menghasilkan tiga kelompok produk secara bersamaan (three in one), yaitu minyak nabati, biomassa, dan jasa lingkungan (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2024h). Ketiga produk tersebut merupakan joint product yang dihasilkan secara simultan dan tidak saling meniadakan.
Pemanfaatan ketiga produk tersebut memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yakni pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, serta pengurangan risiko lingkungan termasuk penurunan emisi karbon.
Berikut ini ulasan mengenai bukti kontribusi dan fungsi industri kelapa sawit baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Aspek Ekonomi. Minyak kelapa sawit memiliki keunggulan dalam hal produktivitas, yakni sekitar empat hingga tujuh kali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan minyak nabati utama lain (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021c). Keunggulan tersebut menjadikan pasokan minyak sawit tersedia dalam jumlah yang relatif besar (availability) serta stabil sepanjang tahun (stability) sehingga berdampak pada harga yang lebih kompetitif (affordability).
Kondisi tersebut memberikan manfaat signifikan bagi konsumen, baik di negara produsen maupun negara importir terutama bagi negara-negara berpendapatan rendah atau negara berkembang karena dapat memperoleh minyak sawit dan produk turunan dengan harga yang lebih terjangkau (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2021d; 2024b).
Kontribusi industri kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat diamati pada berbagai tingkatan, mulai dari lokal, regional, nasional, hingga global (Susila, 2004; World Growth, 2011; Kasryno, 2015; Euler et al., 2016; Edwards, 2019; PASPI, 2022; 2023). Pada tingkat lokal perkebunan kelapa sawit berperan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, baik bagi petani maupun tenaga kerja di perusahaan perkebunan.
Peningkatan pendapatan di wilayah perkebunan kelapa sawit memicu aktivitas ekonomi baru melalui berbagai transaksi dan perputaran uang di masyarakat. Hal ini menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) serta dampak limpahan ekonomi (economic spillovers) (Dib et al., 2018) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Rifin, 2011; PASPI Monitor, 2023e).
Pada tingkat nasional, industri kelapa sawit memegang peranan penting sebagai sumber devisa utama yang berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia (PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2022; 2023a; 2024a; 2025f). Sementara pada tingkat global, kontribusi ekonomi industri sawit tercermin dari peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak di negara-negara importir yang diperoleh melalui kegiatan impor dan hilirisasi produk sawit (European Economics, 2016; Shigetomi et al., 2020; PASPI Monitor, 2021b).
Aspek Sosial. Perkebunan dan industri kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja pada tingkat lokal dan regional (Susila, 2004; Syahza, 2005, 2013; Rist et al., 2010; Qaim et al., 2020; Kasryno, 2015; Dib et al., 2018; TNP2K, 2019; PASPI, 2023).
Pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah pedesaan turut mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta sarana ekonomi lokal (Budidarsono et al., 2012; Krishna et al., 2017; Setiawan, 2019; Edwards, 2019; Santika et al., 2019; Chrisendo et al., 2021; Syahza et al., 2021), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Pada skala global kegiatan impor dan hilirisasi minyak sawit juga memberikan dampak ekonomi positif, khususnya dalam bentuk penyerapan tenaga kerja (job creation) di negara-negara importir (European Economics, 2016; PASPI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa industri sawit tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi lintas negara melalui rantai pasok global.
Selain kontribusi ekonomi, perkebunan kelapa sawit memiliki fungsi sosial budaya yang penting. Kehadiran industri sawit telah mendorong pembentukan keragaman etnis dan sosial di wilayah-wilayah sentra produksi, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Fenomena ini terjadi karena mobilitas penduduk dari berbagai suku dan daerah baik melalui program transmigrasi maupun migrasi mandiri untuk bekerja sebagai petani sawit, karyawan perusahaan perkebunan, maupun di sektor-sektor ekonomi pendukung lain.
Kehadiran masyarakat multietnis tersebut menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai ruang interaksi sosial dan budaya yang dinamis sekaligus wadah pelestarian keragaman sosial di tingkat lokal. Selain itu, heterogenitas sosial di kawasan perkebunan sawit mendorong terbentuknya modal sosial bridging seperti collective action (PASPI, 2022).
Salah satu wujud nyata dari collective action tersebut adalah pembentukan koperasi dan kemitraan antara pelaku usaha perkebunan yang berperan dalam memperkuat kolaborasi ekonomi serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan sawit.
Aspek Lingkungan. Perkebunan kelapa sawit memiliki kemampuan sebagai penyerap karbon (carbon sink), bahkan nilai net carbon sink-nya tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan hutan tropis (Henson, 1999; PASPI, 2023; PASPI Monitor, 2023b, 2023g, 2023i). Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lain seperti kedelai, rapeseed, dan biji bunga matahari, kelapa sawit dinilai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) (PASPI, 2023).
Hal ini disebabkan oleh karakteristik kelapa sawit yang lebih hemat dan efisien dalam penggunaan lahan, memerlukan air dalam jumlah relatif lebih sedikit (FAO, 2013; Gerbens-Leenes et al., 2009), serta menghasilkan polutan air dan tanah yang lebih rendah (FAO, 2013).
Selain itu, kelapa sawit memiliki tingkat kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss) yang lebih rendah dan emisi gas rumah kaca yang lebih hemat apabila dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lain (Beyer et al., 2020; Beyer dan Rademacher, 2021; PASPI Monitor, 2024b).