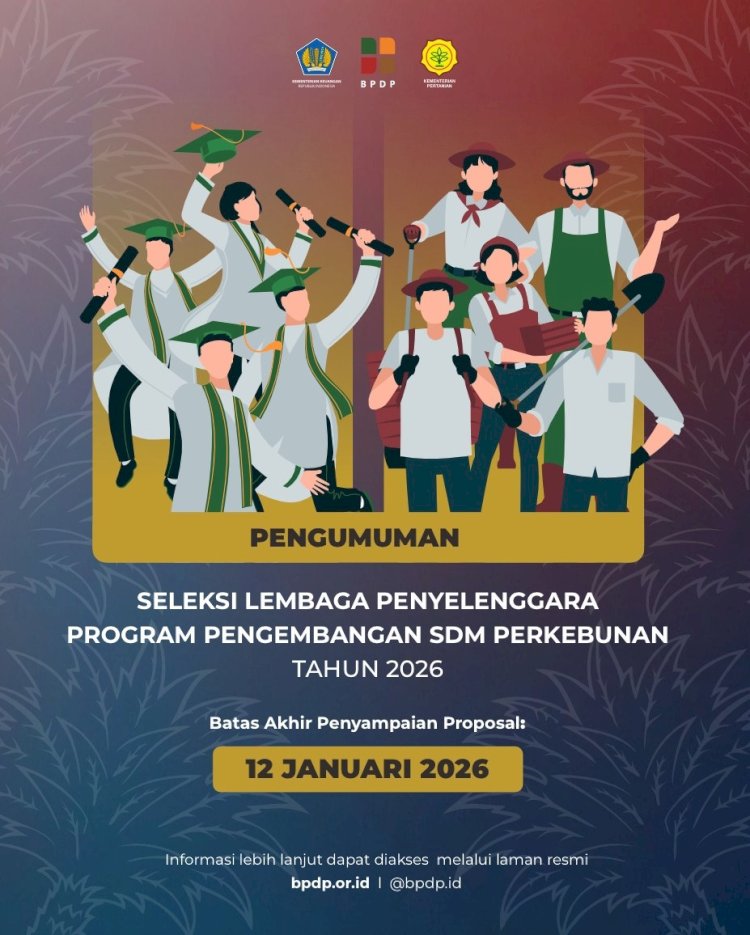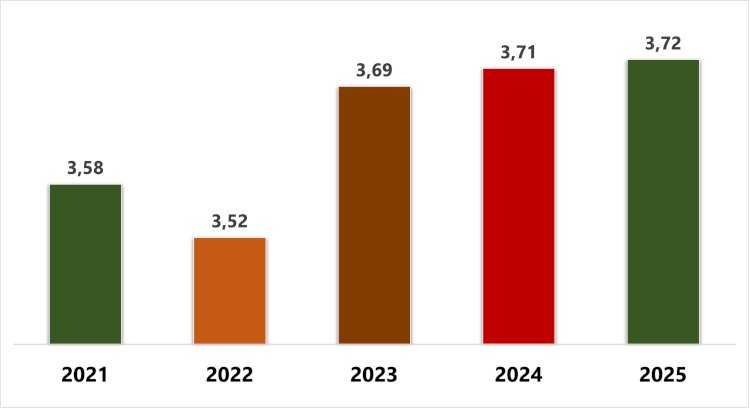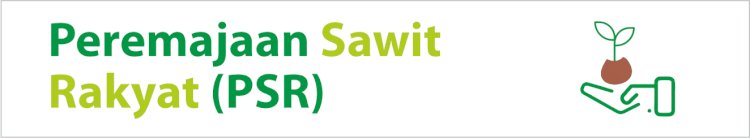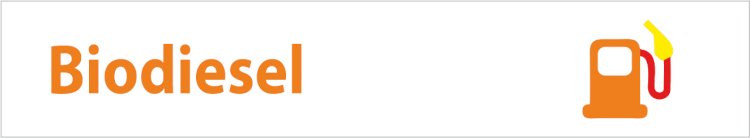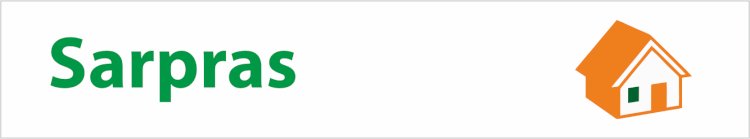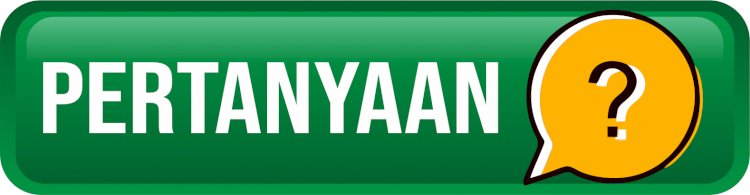Perkebunan Sawit Merupakan Lokomotif Ekonomi yang Inklusif
Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di suatu kawasan kerap menjadikan kawasan tersebut sebuah agropolitan (kota-kota baru pertanian) karena mendorong kehadiran pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain.

Sejak awal tahun 1980-an, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik sebagai bagian dari pembangunan pertanian maupun pengembangan daerah (transmigrasi) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, ditujukan untuk membuka dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan.
Program pemerintah tersebut tidak hanya dilakukan di daerah pelosok, tetapi juga memanfaatkan lahan semak belukar, lahan terlantar, dan bekas logging yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (PASPI, 2020 berjudul Kebun Sawit Indonesia Bukan Penyebab Deforestasi, Justru Menghijaukan Kembali Ekonomi, Sosial, dan Ekologi Lahan Terlantar).
PASPI (2020) dalam jurnal berjudul Inklusivitas Perkebunan Sawit memaparkan, pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam konteks pembangunan kawasan pedesaan merupakan kegiatan ekonomi pioneer sekaligus juga menjadi kegiatan reforestasi yang menghijaukan kembali ekonomi masyarakat di wilayah yang rusak akibat logging pada masa sebelumnya.
Daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi, terbelakang atau lahan terdegradasi dalam bentuk semak belukar yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dikembangkan oleh perusahaan perkebunan negara/BUMN dan/atau swasta sebagai inti dan masyarakat lokal sebagai plasma dalam suatu kerja sama PIR atau bentuk kemitraan yang lain.
Mengingat daerah yang bersangkutan masih terisolasi maka perkebunan swasta/BUMN harus membuka jalan/jembatan masuk (access road), pembangunan jalan usaha tani (farm road), pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan fasilitas sosial/umum.
Kemitraan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan yang sebelumnya hanya terjadi antara perkebunan sawit swasta dan BUMN dengan perkebunan sawit rakyat (plasma dan mandiri) juga telah menarik perkembangan sektor ekonomi lain di pedesaan, seperti mendorong berkembangnya usaha kecil menengah koperasi (UKMK) yang bergerak pada sektor supplier barang/jasa industri perkotaan maupun pedagang hasil-hasil pertanian/perikanan/peternakan untuk kebutuhan pangan masyarakat perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2020).
Dalam bahasa ekonomi, kemitraan sawit tersebut menciptakan multiplier effect, di mana peningkatan pendapatan masyarakat perkebunan akan meningkatkan konsumsi produk pangan yang dihasilkan oleh petani pangan/peternak/nelayan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan dari kelompok masyarakat lokal yang menyuplai produk pangan tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan PASPI dalam jurnal yang sama, pada tahap selanjutnya, pertumbuhan perkebunan sawit setelah menghasilkan minyak sawit (CPO) di kawasan tersebut berkembang menjadi pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian).
Pengembangan perkebunan kelapa sawit menarik investasi baru ke daerah terisolir di pedesaan sehingga dapat mengubah daerah terbelakang menjadi pusat pertumbuhan baru.
Hal tersebut juga terkonfirmasi oleh studi World Growth (2011) berjudul The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah bagian penting dari pembangunan pedesaan.
Temuan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian empiris yang telah menunjukkan bukti bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit di pedesaan memberikan manfaat pada perekonomian pedesaan. Supriadi (2013) dalam jurnal berjudul Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sambas menyatakan bahwa pembangunan perkebunan sawit telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Kondisi tersebut meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rumah tangga dan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Perputaran uang yang terjadi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa.
Bukti lain yang menunjukkan perkebunan sawit sebagai lokomotif ekonomi yang inklusif adalah berkembangnya daerah pelosok yang sepi dan terbelakang menjadi pusat ekonomi baru sebagai suatu agropolitan. Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014), hingga periode 2013, setidaknya terdapat 50 kawasan pedesaan terbelakang/terisolir yang telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis sentra produksi minyak sawit.
Daftar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah akibat pembangunan perkebunan sawit tersebut terbagi pada delapan provinsi di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut.
1. Sumatera Utara (Stabat, Belarang, Sei Rampah, Limapuluh, Perdagangan, Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara, Kota Pinang, Sosa, Sibuhuan, Panyabungan, dan lain-lain);
2. Riau (Pasir Pengaraian, Bangkinang, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Teluk Kuantan, Dumai, Pekanbaru, dan lain-lain);
3. Sumatera Selatan (Sungai Lilin, Tugumulyo, Pematang Panggang, Bayung Lencir, Musi Rawas, Peninjauan, Muara Enim, Lahat);
4. Jambi (Sarolangun, Sungai Bahar, Sengeti, Kuala Tungkal, dan lainnya);
5. Kalimantan Tengah (Sampit, Kuala Pembuang, Pangkalan Bun, Kasongan, dan lainnya);
6. Kalimantan Timur (Sangatta, Tenggarong, Tana Pase, Tanjung Redeb, Nunukan, Sendawar, dan lainnya);
7. Kalimantan Selatan (Batulicin, Kotabaru, Pelaihari, dan lainnya);
8. Sulawesi (Mamuju, Donggala, Bungku, Luwu, Pasangkayu, dan lainnya).
Hal ini berarti manfaat ekonomi yang diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat pelaku/bekerja pada perkebunan kelapa sawit.
Akan tetapi, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit juga dinikmati oleh masyarakat di pedesaan yang bekerja sebagai supplier produk pangan. Kondisi ini menunjukkan perkebunan sawit adalah sektor ekonomi yang inklusif.