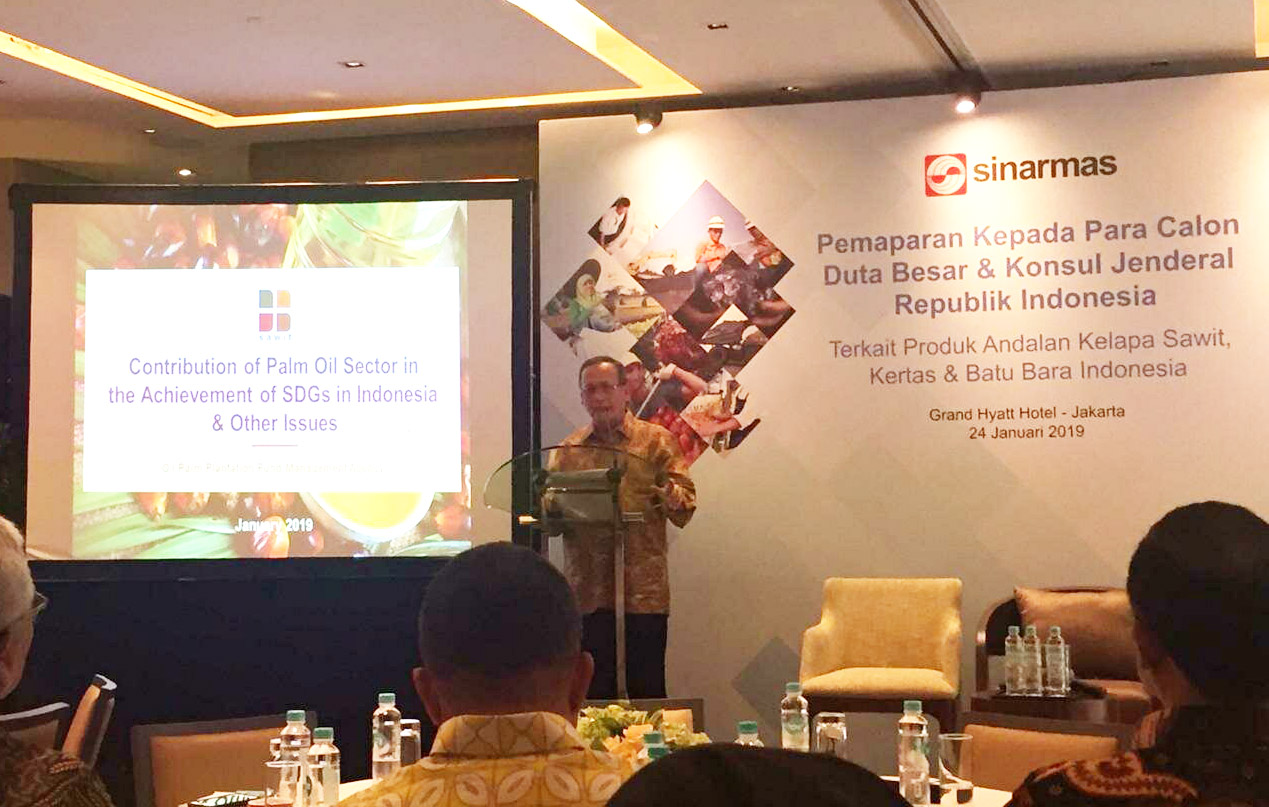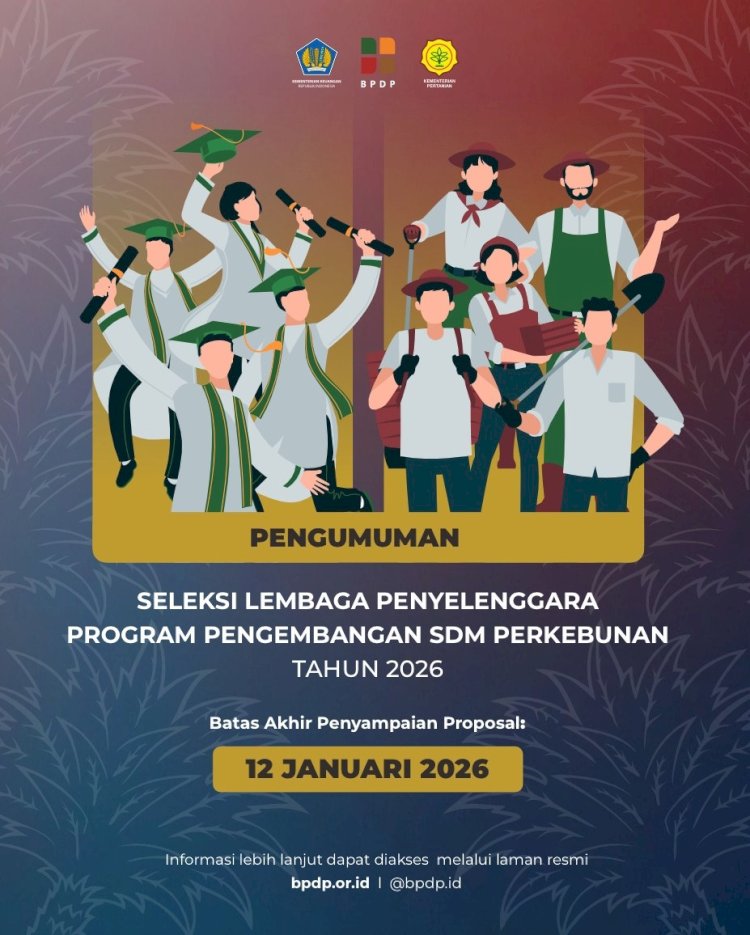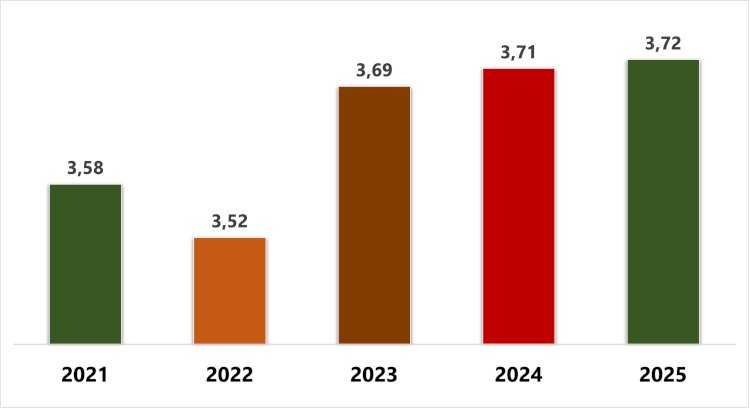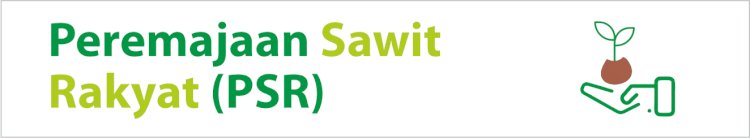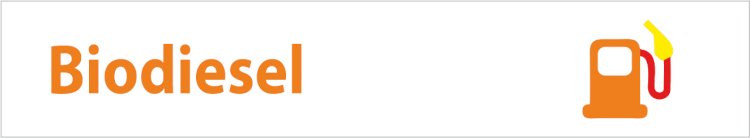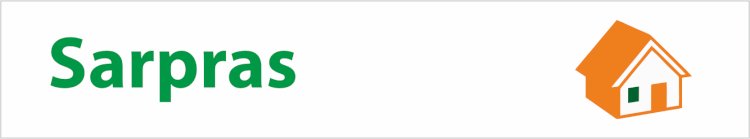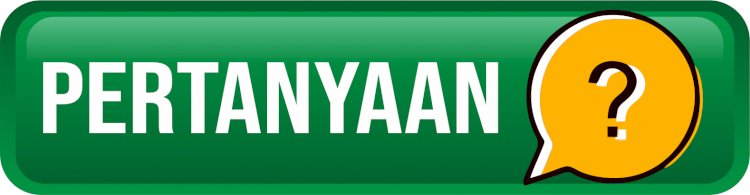Kelapa Sawit sebagai Tanaman Penyerap Karbon Terbaik di Dunia
Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon terbaik di dunia.

Perubahan iklim global telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia dengan peningkatan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu penyebab utama fenomena tersebut. Upaya mitigasi perubahan iklim tidak hanya menitikberatkan pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga mencakup strategi peningkatan kapasitas penyerapan karbon dari atmosfer. Dalam konteks tersebut, kelapa sawit (elaeis guineensis) dipandang sebagai salah satu tanaman yang memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon terbaik di dunia.
PASPI (2025) menjelaskan, tanaman kelapa sawit menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer melalui proses fotosintesis asimilasi. Dalam proses tersebut, tanaman kelapa sawit menyerap CO₂ dari atmosfer bumi (Hardter et.al., 1997; Henson, 1999; Fairhurst dan Hardter, 2003) kemudian menyimpannya menjadi stok karbon dalam bentuk biomassa baik yang berada di atas tanah (above ground biomass) maupun di bawah tanah (below ground biomass).
Kelapa sawit memiliki sejumlah karakteristik yang menjadikannya sebagai tanaman penyerap karbon yang sangat efisien, antara lain: (1) pertumbuhan yang cepat disertai dengan biomassa yang besar, (2) kanopi yang lebar dengan luas permukaan daun tinggi, (3) produksi tinggi dengan siklus hidup yang panjang yaitu sekitar 25–30 tahun, serta (4) sistem perakaran yang dalam dan luas sehingga mampu menyerap karbon secara berkelanjutan dan menyimpan dalam jangka panjang.
Studi yang dilakukan oleh Fortasbi (2025) menunjukkan bahwa bagian tanaman kelapa sawit yang berkontribusi paling besar terhadap penyerapan karbon adalah batang. Batang kelapa sawit mampu menyerap karbon sebesar 29,13 ton per hektare dari total 39,94 ton karbon per hektare yang diserap oleh tanaman berusia 25 tahun.
PASPI Monitor (2025) dalam jurnal berjudul Sawit, Penyerap Karbon Terbaik di Dunia mengatakan kelapa sawit memiliki potensi signifikan sebagai penyerap karbon di dunia dengan kapasitas penyerapan mencapai 64,5 ton karbon per hektare per tahun. Apabila dikalikan dengan total luas perkebunan di Indonesia maka kontribusi agregat kelapa sawit dalam mengurangi emisi karbon menjadi sangat signifikan. Hal tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dalam upaya memitigasi perubahan iklim global.
Kapasitas tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan penyerapan karbon pada ekosistem hutan tropis maupun teknologi penyerapan karbon buatan seperti direct air capture. Berikut ini ulasan perbandingan antara kelapa sawit dengan hutan tropis dan direct air capture yang dirangkum dari jurnal PASPI tersebut.
Perbandingan dengan Hutan Tropis. Berdasarkan studi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2023), hutan tropis hanya mampu menyerap sekitar 25 ton karbon per hektare per tahun. Adapun, Henson (1999) melaporkan dalam sebuah studi bahwa kelapa sawit memiliki kapasitas penyerapan karbon yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hutan tropis.
Salah satu alasan utama perbedaan tersebut adalah karakteristik ekosistem masing-masing. Hutan tropis didominasi oleh vegetasi yang telah mencapai usia matang atau tua sehingga laju fotosintesisnya relatif mendekati laju respirasi. Sebaliknya, perkebunan kelapa sawit umumnya terdiri atas tanaman yang berada dalam fase pertumbuhan aktif sehingga aktivitas fotosintesis dan kemampuan penyerapan karbon lebih optimal.
Perbandingan dengan Direct Air Capture (DAC). Teknologi DAC merupakan inovasi yang dikembangkan untuk menangkap CO₂ langsung dari udara. Meskipun menjanjikan, teknologi ini masih memiliki biaya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan metode alami seperti penyerapan karbon oleh tanaman kelapa sawit.
PASPI (2025) merangkum dari berbagai sumber bahwa biaya penyerapan satu ton CO₂ melalui kelapa sawit berada pada kisaran US$5 hingga US$15 atau sekitar Rp82.000 hingga Rp246.000 per ton CO₂. Sementara itu, biaya yang dibutuhkan oleh teknologi DAC mencapai US$500 hingga US$1.000, setara dengan Rp8.205.000 hingga Rp16.410.000 per ton CO₂.
Selain itu, teknologi DAC saat ini memerlukan input energi yang sangat besar untuk operasinya, yaitu sekitar 1.500–2.500 kWh per ton CO₂, sedangkan kelapa sawit lebih efisien karena memanfaatkan energi matahari melalui proses fotosintesis alami.
Uraian di atas menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit secara bersih (neto) berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink). Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari solusi global dalam upaya menurunkan emisi karbon di atmosfer bumi.
Kontribusi perkebunan kelapa sawit dapat diwujudkan melalui dua mekanisme sekaligus, yaitu (1) menyerap kembali karbon dioksida dari atmosfer bumi melalui proses fotosintesis dan (2) mengurangi emisi karbon dioksida dengan mengganti (substitusi) energi fosil boros emisi dengan biofuel sawit yang hemat emisi.