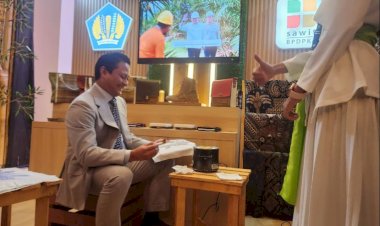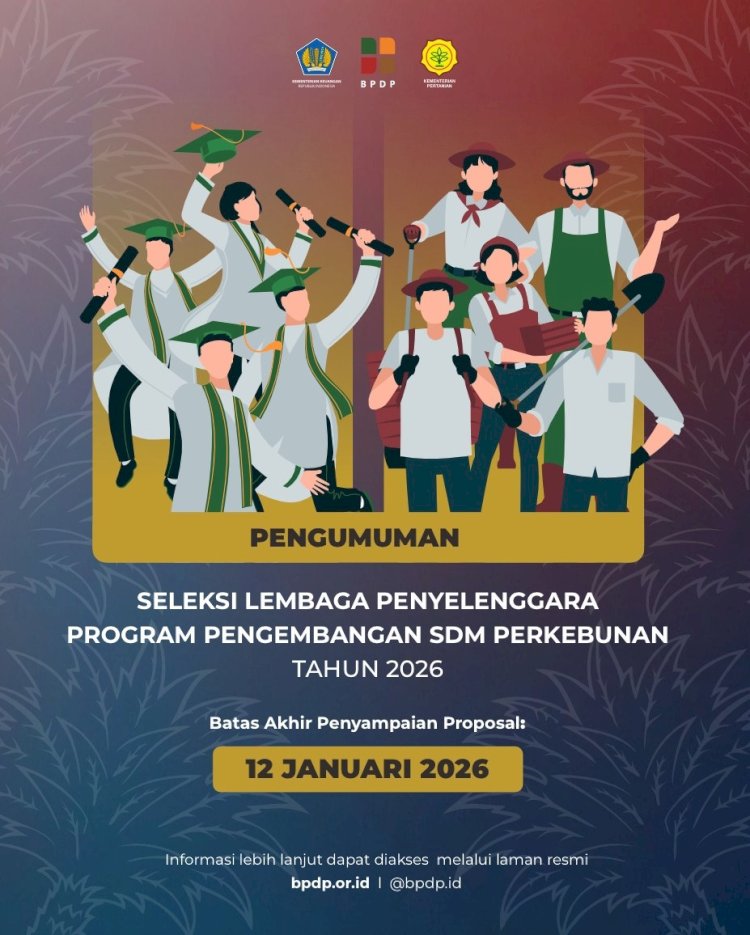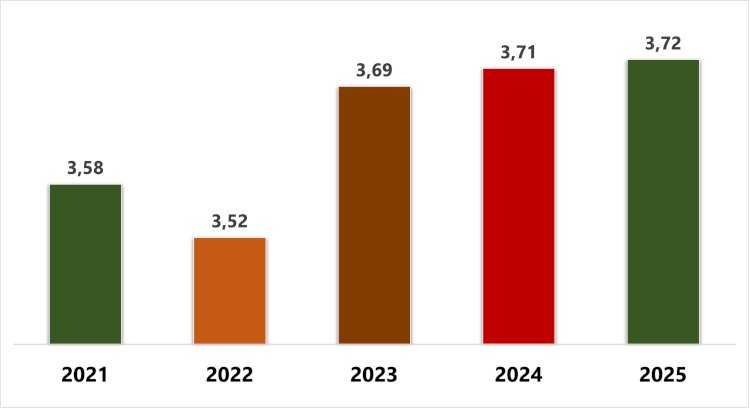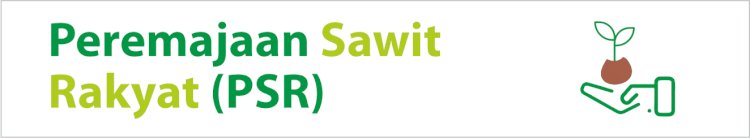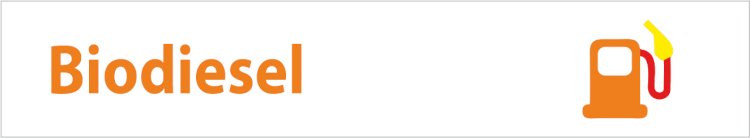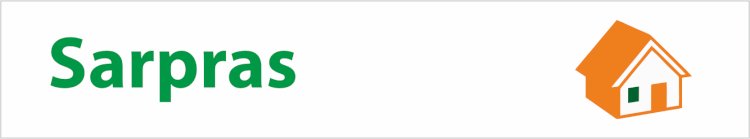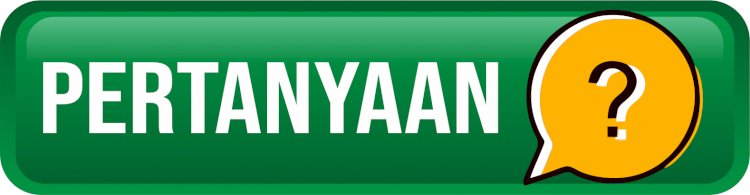Mengenal Aspek Keberlanjutan Minyak Sawit
Aspek keberlanjutan dalam produksi dan pengelolaan minyak sawit menjadi faktor krusial dalam mendukung kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan minyak sawit yang luas dalam industri pangan global dengan tingkat konsumsi yang mencakup hampir seluruh negara di dunia menjadikan masyarakat internasional semakin bergantung pada komoditas tersebut (Shigetomi et al., 2020). Oleh karena itu, aspek keberlanjutan (sustainability) dalam produksi dan pengelolaan minyak sawit menjadi faktor yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mendukung kelestarian lingkungan.
Perkembangan industri minyak sawit global yang sangat pesat sering dikaitkan dengan perubahan tata guna lahan (land use change), termasuk di dalamnya isu deforestasi (Vijay et al., 2016; European Union, 2013) serta hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss) sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah penelitian (Koh & Wilcove, 2008; Fitzherbert et al., 2009; Foster et al., 2011; Savilaakso et al., 2014; Austin et al., 2019).
PASPI Monitor (2022) dalam jurnal berjudul Ketahanan Pangan Minyak Nabati Global Berkelanjutan menegaskan bahwa permasalahan deforestasi, perubahan tata guna lahan, emisi, dan penurunan keanekaragaman hayati pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan industri minyak sawit melainkan juga relevan pada berbagai komoditas, sektor, dan negara, bahkan lintas peradaban.
Dalam konteks penyediaan minyak nabati dan lemak dunia, pertanyaan utama terkait keberlanjutan bukanlah sekadar apakah deforestasi atau emisi terjadi atau tidak, melainkan lebih pada komoditas tanaman penghasil minyak nabati mana yang paling efisien dalam penggunaan lahan, menghasilkan emisi dan polusi paling rendah, serta memiliki dampak biodiversity loss paling kecil?
Berikut ini ulasan mengenai keunggulan minyak sawit dalam hal keberlanjutan apabila dibandingkan dengan berbagai minyak nabati utama lain. Ulasan mengenai aspek keberlanjutan ditinjau dari berbagai indikator yang meliputi indeks deforestasi, keanekaragaman hayati, emisi karbon, serta kebutuhan air.
Indeks Deforestasi. Berdasarkan data mengenai luas areal dan produktivitas berbagai jenis minyak nabati dunia maka dapat diidentifikasi secara implisit perbandingan intensitas deforestasi antar-komoditas minyak nabati utama dunia. Dengan asumsi bahwa semua ekspansi minyak nabati merupakan suatu deforestasi maka indeks deforestasi minyak kedelai mencapai 956 persen, minyak rapeseed 614 persen, minyak biji bunga matahari 827 persen, dan minyak sawit 150 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks produksi minyak nabati global maka tingkat deforestasi yang terkait dengan minyak sawit relatif paling rendah apabila dibandingkan dengan minyak nabati lain. Dengan demikian, keberadaan minyak sawit dalam rantai pasok minyak nabati global berkontribusi terhadap penghematan lahan dan berpotensi mencegah deforestasi dalam skala yang lebih luas (PASPI Monitor, 2021e).
Indeks Keanekaragaman Hayati. Studi yang dilakukan oleh Beyer et al. (2020) serta Beyer dan Rademacher (2021) membandingkan biodiversity loss secara global antar-berbagai jenis minyak nabati. Studi tersebut menilai perubahan biodiversitas berdasarkan perbandingan tutupan lahan sebelum dan sesudah dikonversi menjadi lahan perkebunan tanaman penghasil minyak nabati. Sebagai indikator, penelitian tersebut menggunakan ukuran footprint Species Richness Loss (SRL) per liter minyak yang dihasilkan untuk menggambarkan tingkat kehilangan keanekaragaman hayati.
Dengan menggunakan SRL minyak sawit sebagai tolok ukur (benchmark), studi tersebut menunjukkan bahwa SRL minyak kedelai mencapai 184 persen lebih tinggi dibandingkan dengan SRL minyak sawit. Selanjutnya, SRL minyak rapeseed tercatat 179 persen lebih tinggi. Adapun, SRL minyak biji bunga matahari mencapai 144 persen lebih tinggi dibandingkan dengan minyak sawit.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila SRL dijadikan indikator untuk mengukur biodiversity loss maka minyak sawit merupakan jenis minyak nabati dengan tingkat kehilangan keanekaragaman hayati paling rendah (PASPI Monitor, 2021g). Sebaliknya, minyak kedelai tercatat sebagai minyak nabati dengan biodiversity loss tertinggi. Dengan demikian, untuk setiap liter minyak yang dihasilkan maka minyak sawit memiliki dampak kehilangan keanekaragaman hayati paling kecil di dunia.
Indeks Emisi Karbon. Studi yang dilakukan oleh Beyer et al. (2020) serta Beyer dan Rademacher (2021) menemukan bahwa pada tingkat ekosistem global, perkebunan kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati dengan tingkat emisi terendah apabila dibandingkan dengan sumber minyak nabati lain (PASPI Monitor, 2021h).
Dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan perkebunan sawit untuk setiap liter minyak maka emisi minyak kedelai tercatat 425 persen lebih tinggi, emisi minyak rapeseed 242 persen lebih tinggi, dan emisi minyak biji bunga matahari 225 persen lebih tinggi. Indeks emisi berbagai jenis minyak nabati lain tercatat juga jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan minyak sawit. Indeks emisi minyak kacang tanah mencapai 424 persen, minyak kelapa 337 persen, dan minyak zaitun (olive oil) sebesar 342 persen (PASPI Monitor, 2021h).
Dengan demikian, apabila diurutkan berdasarkan tingkat emisi terendah hingga tertinggi maka peringkat minyak nabati adalah sebagai berikut: (1) minyak sawit, (2) minyak biji bunga matahari, (3) minyak rapeseed, (4) minyak zaitun, (5) minyak kelapa, (6) minyak kedelai, dan (7) minyak kacang tanah.
Indeks Kebutuhan Air. Gerbens-Leenes et al. (2009) serta Mekonnen & Hoekstra (2010) mengemukakan bahwa tanaman penghasil minyak nabati dengan kebutuhan air tertinggi adalah tanaman rapeseed, diikuti oleh kelapa, ubi kayu, jagung, kedelai, dan bunga matahari. Untuk menghasilkan setiap satu giga joule (GJ) bioenergi berupa minyak, tanaman rapeseed memerlukan sekitar 184 meter kubik air.
Sementara itu, tanaman kelapa yang banyak dibudidayakan di Indonesia, Filipina, dan India memerlukan rata-rata sekitar 126 meter kubik air, sedangkan tanaman ubi kayu yang menjadi sumber etanol membutuhkan rata-rata sekitar 118 meter kubik air.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelapa sawit termasuk salah satu tanaman penghasil bioenergi yang paling efisien dalam penggunaan air, menempati posisi kedua setelah tebu. Tanaman kedelai membutuhkan rata-rata sekitar 100 meter kubik air untuk menghasilkan setiap satu GJ bioenergi. Sementara itu, kelapa sawit hanya memerlukan sekitar 75 meter kubik air untuk menghasilkan jumlah energi yang sama. Dengan demikian, minyak sawit dapat dikategorikan sebagai minyak nabati paling efisien dalam penggunaan air (PASPI Monitor, 2021f).
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa minyak sawit merupakan komoditas minyak nabati yang paling berkelanjutan apabila dibandingkan dengan berbagai jenis minyak nabati lain. Keberadaan minyak sawit dalam rantai pasok minyak nabati global berperan penting dalam mengurangi potensi deforestasi, emisi, dan kehilangan keanekaragaman hayati dunia secara lebih efektif dibandingkan dengan sumber minyak nabati lain.