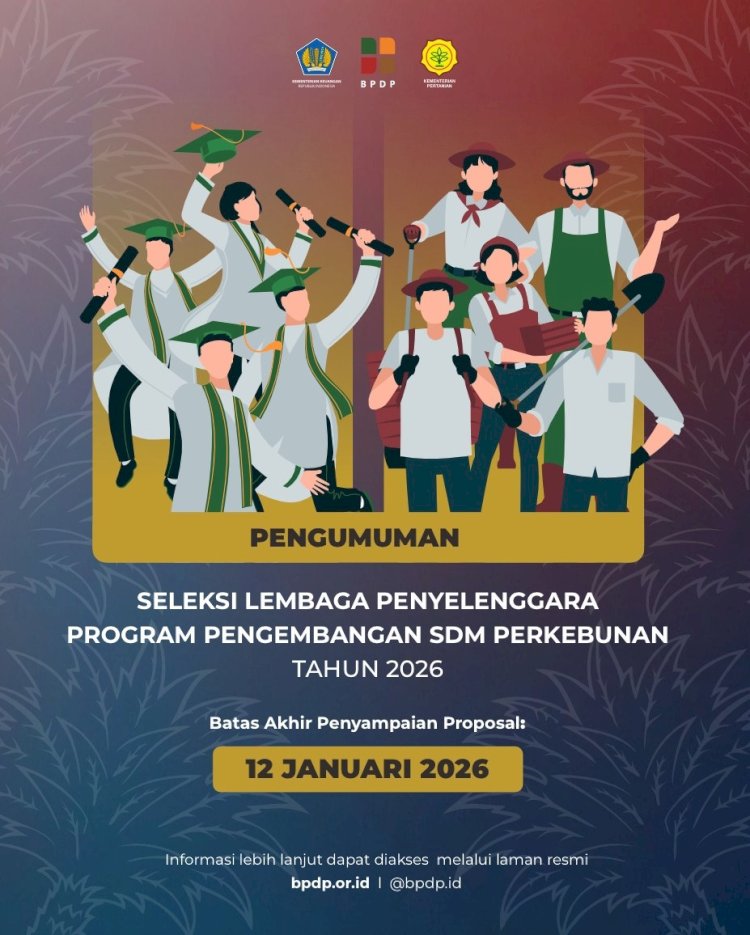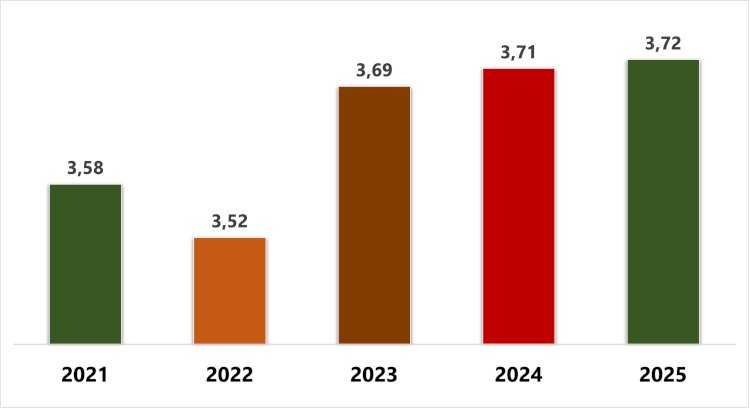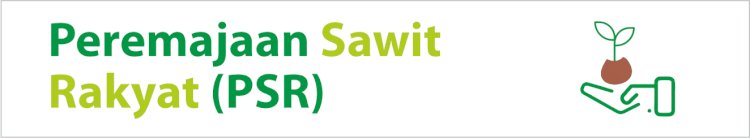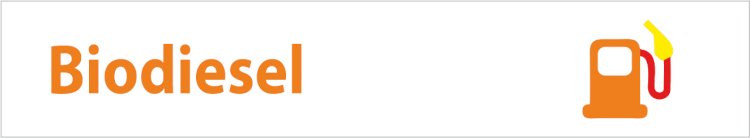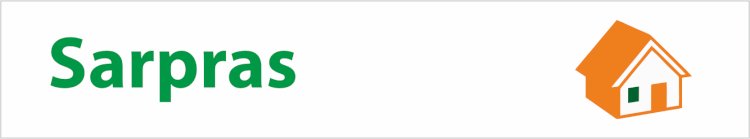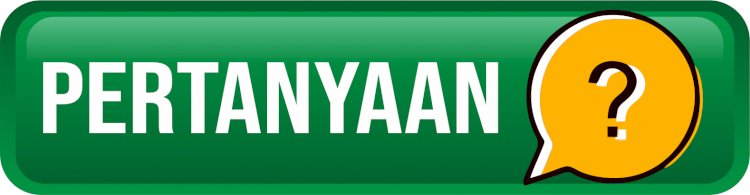Kelapa Sawit Menjadi Bagian dari Konservasi Tanah dan Air

Perkebunan kelapa sawit secara alamiah memiliki kemampuan sebagai tanaman konservasi tanah dan air (Harahap, 2007). Dua mekanisme alamiah konservasi tanah dan air dari perkebunan kelapa sawit adalah mekanisme struktur pelepah daun dan canopy cover, serta mekanisme sistem perakaran tanaman kelapa sawit.
Kedua kemampuan alamiah tersebut ditambah dengan tata kelola atau GAP konservasi tanah dan air yang baik (man-made), menjadikan perkebunan sawit sebagai bagian yang penting dari sistem konservasi tanah dan air pada suatu wilayah (PASPI, 2021 dalam laporan berjudul Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Bagian Integral dari Konservasi Tanah dan Air Wilayah).
Berikut penjelasan secara rinci terkait mekanisme alamiah konservasi tanah dan air dari perkebunan kelapa sawit tersebut yang dikutip dari jurnal PASPI (2021). Pertama, mekanisme struktur pelepah daun pohon kelapa sawit yang berlapis-lapis mampu menaungi lahan (land cover) mendekati 100 persen sejak kelapa sawit berumur muda.
Setiap pohon kelapa sawit menghasilkan sebanyak 18-30 pelepah setiap tahun. Agar proses fotosintesis dan produktivitas yang dihasilkan tanaman optimal, untuk tanaman muda (≤ 8 tahun) jumlah pelepah dipertahankan pada kisaran 48-56 pelepah. Sedangkan pada tanaman tua (> 8 tahun) dipertahankan pada kisaran 40-48 pelepah (Harahap, 2006; Harry et.al., 2016; Turner and Gilbanks, 1974).
Dengan jumlah pelepah yang dipertahankan tersebut akan membentuk sistem kanopi yang memayungi (canopy cover) hampir 100 persen areal perkebunan sawit.
Struktur pelepah daun yang demikian selain berfungsi dalam proses fotosintesis kelapa sawit, juga berfungsi melindungi tanah dari pukulan langsung air hujan. Jika hujan datang, pukulan air hujan tidak langsung menghujam ke tanah, namun terlindungi dan terpecah oleh struktur pelepah daun berlapis-lapis tersebut (PASPI, 2021).
Kedua, tanaman kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut pohon yang masif, luas, dan dalam (Harahap, 1999, 2007, Harianja, 2009). Perakaran kelapa sawit dewasa dapat mencapai radius 4 meter sekeliling pangkal dan memiliki kedalaman hingga 5 meter di bawah permukaan tanah yang membentuk pori-pori mikro dan makro tanah (Harahap, 1999).
Semakin banyak pori-pori mikro dan makro tanah maka akan semakin dewasa umur kelapa sawit. Sistem perakaran kelapa sawit yang masif dan membentuk pori-pori di dalam tanah tersebut berfungsi sebagai penyimpan bahan organik dan cadangan air. Semakin meningkat umur tanaman sawit maka akan semakin luas dan dalam perakarannya sehingga pori-pori tanah yang menyimpan bahan organik dan air tanah juga semakin besar.
Pada tanaman sawit yang sudah dewasa, perakaran kelapa sawit mencapai lebih dari 5 meter dan memiliki kedalaman lebih dari 5 meter dari pangkal batang pohon sawit.
Air yang terisi pada musim hujan dan tersimpan dalam pori-pori tanah di mana kelapa sawit ditanam, dapat menciptakan cadangan air yang cukup besar. Ketika musim kering tiba, cadangan air tersebut dilepas secara perlahan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit sendiri, kebutuhan tanaman lain di sekitarnya, hingga kebutuhan mikroorganisme tanah.
Sebaliknya ketika musim hujan, air hujan yang jatuh ke lahan sawit terserap melalui pori-pori tanah sebagai cadangan air. Sistem biopori alamiah yang demikian menjadikan kebun sawit sebagai tanaman konservasi tanah dan air (PASPI, 2021).
Penelitian (Allen et al.,1998; Rusmayadi, 2011) juga membuktikan bahwa kapasitas penyimpanan air pada lahan sawit lebih baik dibandingkan tanaman karet, sehingga kandungan air tanah di lahan sawit lebih tinggi daripada lahan yang ditanami karet.
Biopori alamiah tersebut meningkatkan kemampuan lahan kebun sawit dalam menyerap/menahan air (water holding capacity) melalui peningkatan penerusan (infiltrasi) air hujan kedalam tanah, mengurangi aliran air permukaan (water run-off), dan menyimpan cadangan air di dalam tanah.
Persentase penerusan curah hujan ke permukaan tanah, laju infiltrasi lapisan solum, dan cadangan air tanah sampai kedalaman 200 cm pada perkebunan sawit relatif sama dibandingkan lahan hutan (Henson, 1999; PPKS, 2005).
Selain menyerap air, biopori-biopori yang terbentuk pada zona perakaran (rhizosphere) tanaman kelapa sawit juga menyimpan bahan organik. Kandungan bahan organik dan C-organik pada zona perakaran kelapa sawit semakin meningkat seiring dengan peningkatan umur tanaman kelapa sawit (Harianja, 2009).