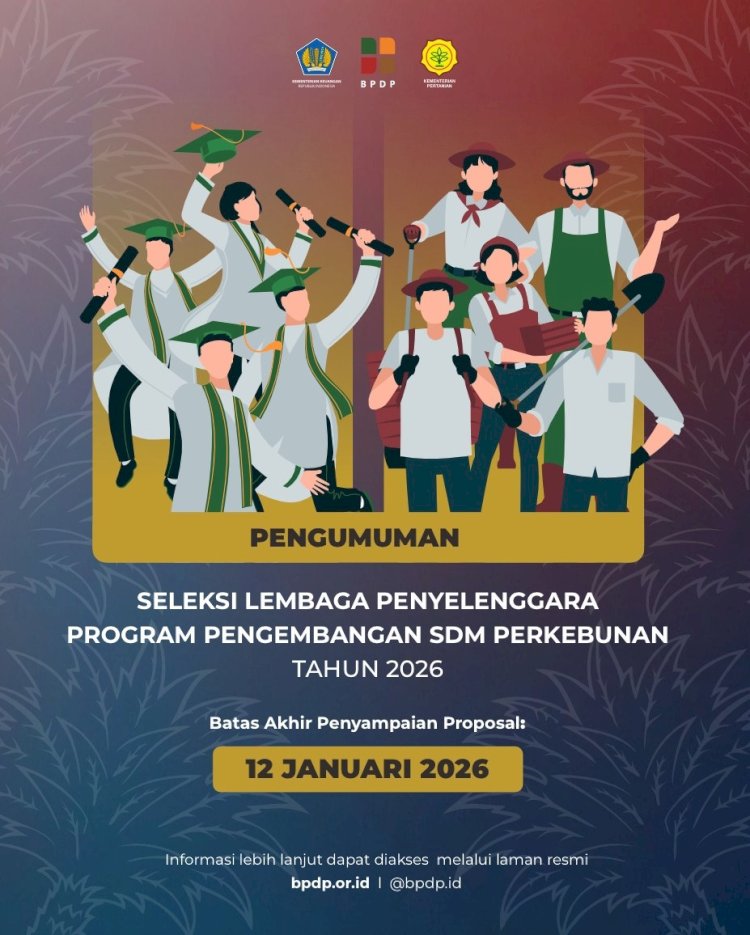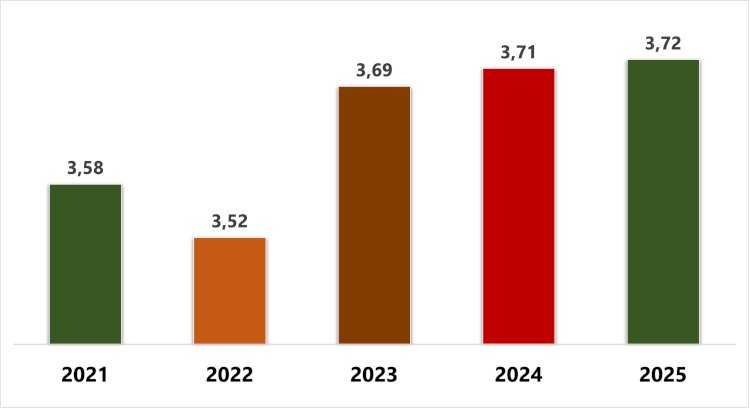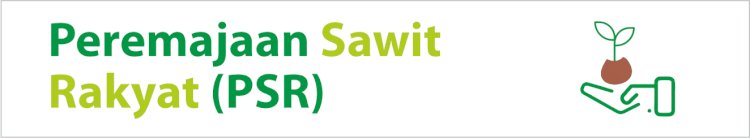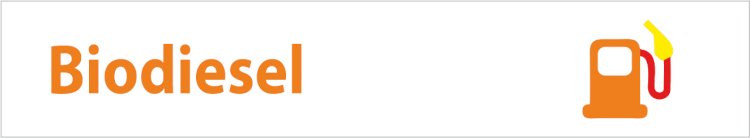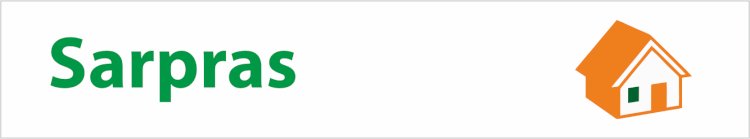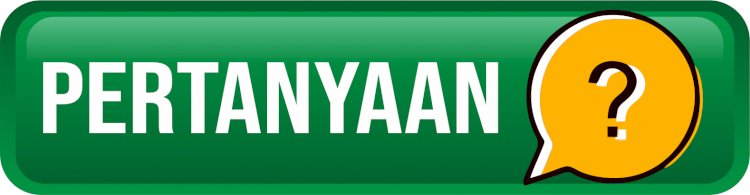Harmonisasi Biodiversitas dan Perkebunan Sawit
Perkembangan luas perkebunan kelapa sawit tidak memiliki kaitan langsung dengan penurunan biodiversitas di Indonesia.

Perkembangan industri perkebunan sawit Indonesia di pasar global membuat banyak pihak anti-sawit semakin gencar membangun framing negatif terhadap industri sawit, salah satunya terkait isu biodiversitas.
Kebun sawit kerap selalu "dikambinghitamkan" sebagai ancaman bagi habitat satwa-satwa liar yang berpotensi menurunkan populasi satwa liar asli seperti orang utan, gajah, dan harimau. Tudingan-tudingan tersebut tentu tidak benar dan tidak berdasarkan fakta objektif. Lantas, seperti apa faktanya?
Habitat Satwa Liar
Berdasarkan laporan International Union for Conservation Nature (IUCN) berjudul Kelapa Sawit dan Keanekaragaman Hayati yang diterbitkan pada tahun 2018, disebutkan bahwa penurunan populasi orang utan dan satwa liar lainnya di Indonesia sudah terjadi sejak lama sebelum pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1970-an.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa perburuan liar, industri pulp dan kertas, serta deforestasi dengan cara pembakaran yang digunakan untuk membuka lahan pertanian skala kecil merupakan ancaman utama bagi populasi orang utan. IUCN mencatat, perburuan telah menjadi pemicu utama menurunnya populasi orang utan lokal di Pulau Borneo selama 200 tahun terakhir.
Sementara itu, studi Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) berjudul Kebun Sawit Berjaya, Biodiversitas Indonesia Tetap Kaya dan Terjaga yang diterbitkan oleh Palm Oil Journal tahun 2020, juga memperkuat temuan bahwa hampir 44 persen hutan yang digolongkan menjadi hutan konservasi dan hutan lindung merupakan "rumah" dan habitat alamiah (in situ) bagi satwa liar tersebut.
Sementara itu, kebun sawit (dan sektor lainnya termasuk pemukiman dan pertanian) berada pada kawasan yang berbeda dan terpisah dengan habitat alamiah satwa liar.
Sistem Pelestarian Biodiversitas Indonesia
Sejak awal pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan pembangunan nasional dengan menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan antar-sektor, baik sektor pengembangan maupun sektor konservasi di Indonesia dilakukan berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing.
Melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Indonesia sudah menetapkan minimum 30 persen dari luas daratan sebagai hutan. Aturan tersebut telah dipenuhi yang ditunjukkan dengan sekitar 50 persen dari total daratan atau 94 juta hektare masih dikategorikan hutan dan sebagian besar adalah hutan primer.
Indonesia juga memiliki kebijakan nasional dan meratifikasi konvensi internasional dalam rangka menjaga kelestarian biodiversitasnya. Misalnya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang membagi daratan Indonesia atas dua kawasan yakni kawasan lindung/konservasi dan kawasan budidaya.
Fungsi utama kawasan lindung adalah sebagai pelestarian flora dan fauna, baik secara in situ (sepenuhnya dirawat alam) maupun secara ex situ (kombinasi perawatan alam dan manusia). Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang fungsi utamanya untuk kegiatan masyarakat baik pertanian, perkebunan, hutan produksi, perkotaan, pemukiman, dan lain-lain.
PASPI dalam jurnal berjudul Kebijakan Pelestarian Biodiversitas Indonesia menegaskan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan budidaya tersebut. Berbeda dengan kawasan lindung/konservasi, penggunaan lahan pada kawasan budidaya dapat terjadi konversi antar-sektor.
Kebun sawit yang dikembangkan di kawasan budidaya selain memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga secara keseluruhan berfungsi sebagai pelestarian biodiversitas benih kelapa sawit melalui
pembudidayaan secara lintas generasi.
Harmonisasi Kebun Sawit dan Biodiversitas di Dalamnya
Studi PASPI berjudul Kebijakan Pelestarian Biodiversitas di Indonesia yang diterbitkan oleh Palm Oil Journal tahun 2020 menegaskan, argumen yang mengkaitkan pengembangan kebun sawit dengan penurunan biodiversitas juga tidak memiliki dasar yang cukup kuat.
Berdasarkan buku data Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang diterbitkan oleh KLHK tahun 2018, daratan Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hutan dan non-hutan (area penggunaan lain). Dari sekitar 187,75 juta hektare luas daratan Indonesia terdapat sekitar 93,9 juta hektare hutan di Indonesia atau sekitar 50 persen dari total daratan masih hutan (masih di atas syarat minimal yang ditetapkan undang-undang). Hutan tersebut terdiri dari 46,1 juta hektare hutan primer; 43,1 juta hektare hutan sekunder; dan 4,7 juta hektare hutan tanaman.
Hampir separuhnya hutan yang tersebar di seluruh daratan Indonesia adalah hutan primer yang merupakan habitat alamiah satwa dan tumbuhan liar seperti
gajah, harimau, orang utan, mawas, badak, singa, beruang, berbagai jenis unggas dan lain-lain.
Bahkan, luasnya hutan primer yang dimiliki Indonesia menyebabkan FAO (2016) dalam laporannya yang berjudul Global Forest Resources Assessment 2015: How are the World’s Forests Changing? menggolongkan Indonesia termasuk ke dalam negara Global Top-Ten Countries with Forest Area For Conservation of Biodiversity.